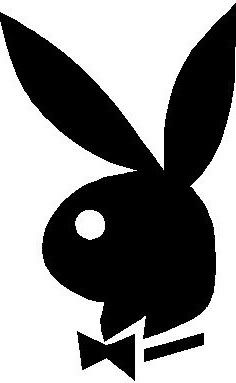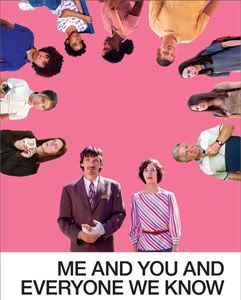Judul : Fearless
Pemain : Jet Li
Sutradara : Ronny Yu
Menonton Fearles bisa jadi adalah momen paling buruk sepanjang karir gue menonton film di bioskop. Kebijakan Djakarta Theater yang langsung memutar film lebih awal dari jadwal tiket membuat gue kehilangan beberapa adegan film biopic tentang perjalanan hidup pendiri klub Wushu Jinwu, Huo Yuanjia ini.
Keterlambatan itu memang bukan tanpa sebab. Gue sebenarnya merasa yakin bisa nyampe di bioskop 5 menit sebelum diputar. Nyatanya, begitu masuk ruangan bioskop sudah gelap. Dan ini lah yang paling memuakkan, gue terpaksa mondar-mandir mencari kursi.
Petugas bioskop mengatakan bahwa kursi gue ada di sebelah kanan paling pojok. Payahnya, dia tidak membimbing gue ke tempat duduk dan membiarkan gue berjalan sendiri. Otomatis, gue pun duduk di tempat yang salah. Yang bikin malu, kejadian salah tempat duduk itu berulang sampai dua kali. Gue jadi terlihat seperti gosokan yang mondar-mandir mencari tempat duduk.
Beruntung, setelah mondar-mandir ada seorang penonton yang berbaik hati menanyakan nomor tempat duduk gue. Ternyata, satu kursi kosong di samping penonton itu adalah kursi saya. Mimpi burukj saya semakin berlanjut karena saya duduk di kursi yang paling depat, tepat di tenga-tengahnya.Akibatnya, saya terpaksa agak melonjorkan badan agar penglihatan saya bisa terasa nyaman.
Secara keseluruhan film Fearless tidaklah berbeda dengan film Jet Li sebelumnya seperti film-film jadulnya yang berjudul Tai Chi Master dan Born To Defence hingga film Jet LI yang pali anyar seperti The One dan Danny The Dog.
Berbeda dengan film Biopic lainnya yang kini tengah marak contoh Walk The Line yang diperani Joaquin Phoenix, film Fearless sama sekali mati rasa ketika bercerita tentang kehidupan Huo Yuanjia sebagai jagoan Kung Fu nomor satu di Cina.
Bahkan dengan film yang temanya hampir sama seperti Fighter in The Wind yang bercerita tentang kehidupan Master Aoyama, dari segi penuturan cerita Fearless benar-benar jauh ketinggalan.
Film terkesan berjalan cepat tanpa mengembangkan atau focus pada kehidupan Huo Yuanjia. Bahkan, kapan Huo Yuanjia benar-benar bisa belajar Kung Fun pun tidak diperlihatkan dengan jelas. Tiba-tiba saja Huo Yuanjia yang berpenyakit asma ini bisa jadi seorang ahli Kung Fu yang ditakuti di Tianjian. Padahal, awalnya Huo Yuanjia tidak boleh belajar Kung Fu atas perintah ayahnya.
Awalnya saya menduga bahwa film ini memang sengaja melompat lebih cepat agar lebih focus pada perjuangan Huo Yuanjia menjadi orang nomor satu. Tapi setelah mengingat beberapa waktu lalu menulis berita Fearles, saya langsung tahu bahwa masa kecil Huo YUanjia adalah salah satu bagian yang paling banyak kena potong.
Wang Bin, salah seorang penulis skenarionya sendiri pernah mengatakan bahwa skrip cerita Fearless sangat lemah. Bahkan, Wang Bin mengatakan bahwa film Fearless tentang hanya cocok untuk dijadikan film di layar televisi.
Entah kenapa saya selalu berpikir bahwa kelemahan terbesar dari Jet Li adalah kemampuannya berakting. Dia memang boleh jago kung fu tapi dia sangat lemah dalam berakting. Sehingga film sebagus apapun, Jet Li tetaplah seorang Jet Li.
Beruntung, Jet Li berhasil menemukan sutradara sehandal Ronny Yu. Sutradara yang pernah menggarap film berjudul Warriors of Virtue dan 51st State ini benar-benar tahu caranya memuaskan penonton.
Ronny tahu bahwa semua orang hanya suka Jet Li ketika berkelahi ketimbang berakting. Tidak heran, kalau dari awal film dimulai tiga buah adegan fighting langsung dimulai. Dan jangan heran puluhan adegan fighting lainnya sudah menunggu sampai film ini selesai.
Selain itu, dengan dukungan sinematograper, Ronny benar-benar berhasil menunjukkan gambar-gambar yang indah serta pergerakan kamera yang benar-benar luar biasa baru. Pergerakan kamera yang dinamis membuat adegan fighting Jet Li benar-benar terasa hidup.
Bukan hanya handal mengambil adegan fighting. Bahkan, scene perubahan musim pun dengan sangat indah ditampilkan oleh Ronny Yu.
Otomatis dengan eksploitasi berlebihan di adega akting plot cerita sama sekali tidak berkembang. Padahal, Jet Li mengatakan bahwa film ini adalah film yang dibuat guna menggugah rasa nasionalisme China.
Sayang, cara yang digunakan Jet Li untuk menggugah perasaan agung itu justru terpendam akibat buruknya akting Jet Li. Beruntung, Jet Li berhasil mengatasi keburukan itu dengan cara-cara yang benar sangat haram dilakukan oleh film-film fighting lainnya.
Terakhir, Jet Li mengatakan bahwa pertarungan bukanlah untuk menjadi seorang jagoan. Pertarungan adalah untuk mencari teman dan persaudaraan. Jangan pernah bertarung untuk dendam, karena dendam hanyalah melahirkan dendam yang paling dahsyat.
Saya rasa pesan itu sangat tepat untuk ditujukan kepada Jet Li. “Jet-Jet jangan bertarung lagi yah. Sama aja ngelihatnya.” Beruntung Jet Li pernah mengatakan bahwa film ini adalah film Kung Fu terakhir yang ia perani.